
AL-QUR'AN adalah firman Allah yang Mahasuci (al-Quddus). Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril: malaikat yang menjadi kepercayaan Allah (al-ruh al-amin). (Qs. al-Syu’ara’ [26]: 193-194) lagi suci (ruh al-quds) (Qs. al-Baqarah [2]: 97-98). Dia diutus oleh Allah untuk membawa Al-Qur’an ke dalam qalb (hati) Rasulullah s.a.w. Oleh karenanya, siapa yang memusuhi Jibril, maka dia kafir dan Allah menjadi “musuhnya”. (Qs. al-Baqarah [2]: 96-97). Karena Al-Qur’an berasal dari Allah yang Maha Suci; dibawa turun oleh malaikat Jibril yang suci; kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang suci, maka Al-Qur’an adalah “Kitab Allah yang Suci”.
Dan umat Islam seluruh dunia meyakini bahwa Al-Qur’an adalah “Kitab Suci”. Anehnya, masih saja ada sarjana Muslim yang tidak rela kaum Muslimin meyakini Al-Qur’an sebagai kitab suci agamanya (Islam). Dengan alasan bahwa Al-Qur’an harus diletakkan dalam “konteks kesejarahan” ketika wahyu ditulis, Al-Qur’an dilucuti dari kesuciannya. (Lihat, Abd Moqsith Ghazali, Luthfi Assyaukanie, dan Ulil Abshar-Abdalla, Metodologi Studi Al-Qur’an [MSA], (Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 3). Ini jelas merupakan satu ide asing (dakh’l) dan murni gaya orientalis dalam melucuri sakralitas Al-Qur’an. Karena mereka mengira bahwa yang menjadikan Al-Qur’an itu suci adalah “konteks sejarah”, bukan Allah ataupun Nabi Muhammad. Untuk itu, pemikiran destruktif dan dekonstruktif ini perlu diluruskan. Agar tidak menjadi virus liar yang menggerogoti keyakinan umat Islam yang sudah “berurat-berakar” dalam ‘nadi keimanan’ mereka. Berikut ini akan dijelaskan kekeliruan pandangan mereka mengenai sakralitas Al-Qur’an.
Masalah Kitab, Mushaf, dan Al-Qur’an
Salah satu nama Al-Qur’an yang ada adalah al-Kitab, karena ia merupakan kitab yang tertulis. Ini pun diakui oleh penulis MSA, karena menurut mereka Al-Qur’an menyebutkannya dalam banyak ayatnya. Meskipun jelas ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa Al-Qur’an itu al-Kitab, mereka tetap “menolak”. Malah berdalih bahwa yang dimaksud oleh Al-Qur’an adalah “tulisan” secara umum. Menurut mereka, hal itu tidak merujuk kepada satu kesatuan kitab suci utuh. Alasan mereka: Karena pada masa Nabi hidup, “sangat tidak masuk akal” membayangkan sebuah kitab suci yang utuh, karena kelengkapan wahyu sangat bergantung kepada usia Nabi. (MSA, hlm. 9).
Apa yang mereka tulis di atas jelas sekali “kerancuannya”. Pertama, menolak firman Allah bahwa Al-Qur’an adalah al-Kitab. Padahal dalilnya sangat jelas. Misalnya dalam Qs. al-Baqarah [2]: 2. Karena kata al-Kitab dalam Qs. 2: 2 ini adalah Al-Qur’an. Karena menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh (w. 1905), maksud dari al-Kitab adalah “satu kitab” yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Dan kitab ini, tegas Ridha, mencakup segala hal yang dibutuhkan bagi para pencari kebenaran (Ïullab al-haqq), petunjuk (al-hidayah), dan bimbingan (al-irsyad) dalam setiap lini kehidupan dunia dan bekal akhirat. Maka Qs. 2: 2 mengisyaratkan itu semua.
Kedua, apakah tidak mungkin kitab itu ada pada zaman Nabi Muhammad? Atau, apakah kitab suci itu harus utuh dulu baru kemudian absah dan valid disebut al-kitab? Pertanyaan ini dijawab dengan tegas oleh Rasyid Ridha: “Tidak mengapa wujud kitab itu belum ada secara keseluruhan (belum lengkap) ketika waktu diturunkan!” Karena keberadaan sebagian kitab tersebut sudah menjadi bukti valid akan kebenarannya. Karena sebagian Al-Qur’an sudah turun sebelum ayat ini turun. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuliskannya.
Bahkan, tambah Ridha, isyarat itu sudah cukup untuk menunjuk kepada surah al-Baqarah. Karena dia benar karena ayatnya diakhir dengan hudan li’l-muttaqan (cukup dan layak menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa). Dan isyarat kepada keseluruhan kandungan al-kitab tersebut ketika turun sebagiannya menegaskan bahwa Allah berjanji kepada Nabi akan melengkapi al-kitab tersebut. Jadi tidak mengapa ketika turun al-kitab tersebut belum ditulis secara utuh. Karena, Anda juga biasa mengatakan: “Saya sedang mendiktekan satu kitab. Atau, kemarilah, akan saya diktekan satu kitab kepadamu!” (Lihat, Rasyid Ridhah, Tafsir al-Manar, 12 Jilid, (Cairo: Dar al-Manar, 1366 H/1947 M, 1: 123). Artinya: buku atau kitab tersebut belum sempurna dituliskan, tapi sudah disebut sebagai kitab.
Jadi, Al-Qur’an adalah al-Kitab. Dan bagi siapa saja yang menelaah kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama kita, tidak akan merasa aneh – apalagi menganggap tak masuk akal – jika Al-Qur’an itu adalah al-kitab. Oleh karena itu, menurut Imam al-Kisa’i, ketika mengomentari kata al-kitab dalam Qs. 2: 2, maksudnya adalah: “Isyarat Al-Qur’an yang berada di langit dan belum turun.” (Lihat, Ibn ‘Athiyyah al-Andalusi, al-Muharrar al-Wajiz, 6 Jilid, (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2001 M, 1: 83). Artinya: menunjukkan bahwa Al-Qur’an adalah al-kitab.
Selain menolak kata al-kitab, penulis MSA juga menolak jika Al-Qur’an merupakan nama bagi Al-Qur’an itu sendiri. Alasan mereka: karena istilah “Al-Qur’an” melewati proses panjang sebelum kitab suci itu dinamakan demikian. (MSA, hlm. 9). Mereka kemudian mencari justifikasi dari kitab al-Itqan karya Imam Jalal al-Din al-Suyuti (w. 911 H). Dimana menurut mereka, sang Imam mencatat bahwa sepeninggal Nabi, para sahabat berbeda pendapat mengenai nama apa untuk menyebut “kitab suci” mereka. Apakah harus disebut “Injil” seperti kaum Kristen, atau “Sifr” seperti dalam tradisi Yahudi.
Padahal, jika kita rujuk langsung ke dalam al-Itqan ceritanya berbeda. Para sahabat berbeda pendapat dalam masalah penyebutan Al-Qur’an bukan sepeninggal Nabi, melainkan ketika Abu Bakr al-Shiddiq selesai melakukan kodifikasi. (Lihat, al-Suyuthi, al-Itqan, 7 Jilid, (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1426, 2: 344). Jadi, mereka mengusulkan penyebutan untuk kodifikasi yang dilakukan oleh Abu Bakr, bukan untuk menyebut isi dan kandungan Al-Qur’an. Karena namanya Allah langsung yang menyebutkan, bukan buatan para sahabat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat yang menyebut kitab suci kaum Muslimin ini dengan “Al-Qur’an”. (Qs. 56: 77, 73: 20, dan 85: 21).
Jadi, meskipun cerita penyebutan Al-Qur’an dengan Muushaf seperti yang diusulkan oleh Abd Allah ibn Masud tidak serta-merta hal itu menjadi dalil dan dalih bahwa Al-Qur’an sebagai wahyu Allah menjadi tidak sakral. Juga tidak sebaliknya, bahwa kata Mushaf merupakan sakralisasi Al-Qur’an. Karena kitab suci yang agung ini sudah “sakral” sejak semula. Anehnya, istilah Muushaf pun dipermasalahkan. Hanya karena berasal dari bangsa Ethiopia (×abasyah), yang menurut mereka merupakan tradisi Kristen di sana untuk merujuk Injil yang dibukukan. (MSA, hlm. 10). Padahal, Al-Qur’an tidak disebut sebagai MuÎÍaf pun namanya sudah Al-Qur’an dan banyak lagi. Bahkan, menurut Ab al-MaÑÉlÊ ÑAzÊzÊ ibn Abd al-Malik yang dikenal dengan Syaidzalah dalam bukunya al-BurhÉn, Allah menamai Al-Qur’an dengan 55 jenis nama. (al-Suyuthi, al-Itqan, 2: 336).
Jadi, dalam hal ini penamaan Al-Qur’an tidak problem sama sekali. Mungkin karena gaya dan metodologi orientalis dalam melihat Al-Qur’an, maka kesimpulan para penulis MSA ini begitu semangat untuk menyatakan. [hidayatullah.com] penulis: Qosim Nursheha Dzulhadi















































































































































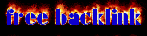
























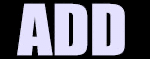



























Tidak ada komentar:
Posting Komentar